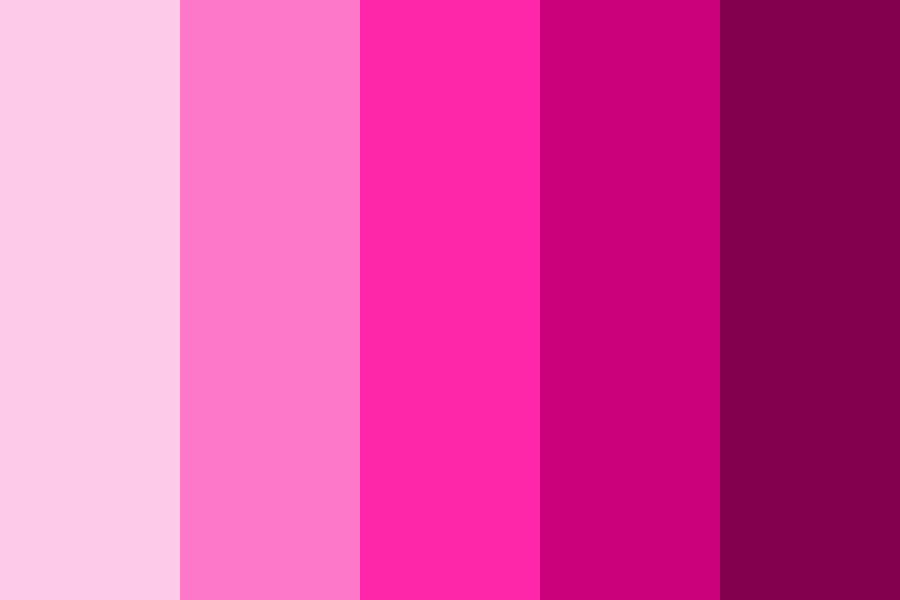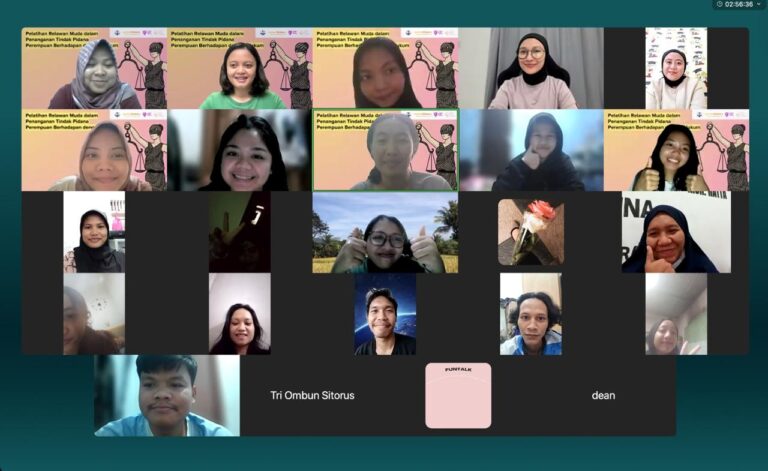Pink selama ini identik dengan kelembutan, kasih sayang, bahkan kepolosan. Ia dilekatkan pada boneka, lipstik, atau ruang domestik perempuan. Tetapi justru karena asosiasi itulah, pink selama puluhan tahun dipakai sebagai alat domestifikasi, mengurung perempuan dalam streotip tunduk dan jinak.
Namun di Aksi di Jakarta saat itu, menjadi makna yang dibalik. Di depan Gedung DPR, seorang ibu berkerudung pink berdiri tegak menghadapi barisan polisi. Adegan itu menjadi ikon politik, pink bukan lagi tanda kepatuhan, melainkan simbol perlawanan. Dari momen inilah lahir pink power, feminitas yang diremehkan patriarki dan kapitalisme, kini berubah menjadi kekuatan politik. Feminitas yang dianggap rapuh justru menjadi ancaman. Pink melawan, bukan menunduk.
Politik kerap kali menjadi sarat dengan simbol. Merah diasosiasikan dengan revolusi, hijau dengan religiusitas, hitam dengan radikalisme. Warna membangun imajinasi kolektif dan memperkuat identitas gerakan. Pink awalnya dipakai untuk membungkus feminitas dalam bingkai jinak, lembut, pasif, dekoratif. Kapitalisme menjual citra itu, sementara patriarki meneguhkan norma bahwa perempuan yang “baik” adalah mereka yang tunduk pada simbol tersebut. Namun feminisme menyabotase simbol itu. Dalam Women’s March di AS, ribuan perempuan mengenakan pussyhat pink untuk mengejek seksisme Donald Trump (Ghodsee & Orenstein, 2021). Di Polandia, atribut pink muncul dalam aksi massa menolak kriminalisasi aborsi (Lipiński, 2018). Di Amerika Latin, pink dipakai untuk melawan kultur macho yang menyusupi negara.
Subversi ini penting, ia menegaskan bahwa perlawanan tidak harus garang dengan warna gelap. Justru warna yang dianggap remeh, manis, dan feminin itulah yang bisa mengacaukan logika kuasa maskulin. Pink mengolok-olok keseriusan wajah negara otoriter, sembari menegaskan bahwa feminitas bisa menjadi kekuatan politik radikal.

Krisis Demokrasi di Indonesia
Pink power di Indonesia lahir di tengah krisis demokrasi. Pasca-Pemilu 2024, demokrasi runtuh di bawah kendali oligarki. Pemilu tak lagi menjadi mekanisme rakyat menentukan masa depan, melainkan transaksi elit untuk membagi kekuasaan dan kekayaan. KPK dilumpuhkan, hukum diperdagangkan, ruang sipil dipersempit dengan represi aparat. Demonstrasi rakyat dijawab dengan gas air mata, jeruji besi, dan pasal karet.
Perempuan menanggung beban paling berat. Buruh perempuan dieksploitasi dengan upah murah, kerja perawatan tetap tak dibayar, tubuh perempuan terus menjadi sasaran kekerasan seksual yang diabaikan negara. Dalam politik elektoral, perempuan hanya diperlakukan sebagai angka keterwakilan, bukan subjek politik. Seperti ditulis Federici, tubuh perempuan selalu menjadi arena perebutan kapitalisme, di Indonesia, ia sekaligus jadi korban otoritarianisme baru.
Di sinilah pink power menemukan relevansinya. Ia lahir dari pengalaman sehari-hari perempuan, dari dapur, pabrik, hingga jalanan, dan meletakkan mereka sebagai subjek politik yang menolak tunduk.
Pink power menandai transformasi feminitas dari simbol yang diremehkan menjadi basis solidaritas baru. Feminitas yang dilecehkan justru menjadi perekat perlawanan. Tetapi pink tidak berhenti pada identitas, ia meluas menjadi perlawanan kolektif terhadap patriarki, kapitalisme, dan otoritarianisme. Dengan mengibarkan pink, perempuan menyatakan diri bukan sekadar objek representasi, melainkan pelaku politik. Mereka menolak politik simbol kosong yang dipakai penguasa untuk membelah rakyat. Bangsa ini terlalu sering dipolarisasi lewat seragam dan warna, sementara oligarki tetap menumpuk kekayaan. Pink power mengingatkan, musuh utama bukan sesama rakyat, melainkan struktur kuasa yang sama-sama menindas.
Pink power menawarkan imajinasi baru tentang perlawanan. Ia menolak dikotomi bahwa kekuatan harus maskulin dan keras. Sebaliknya, kasih sayang, solidaritas, dan empati bisa menjadi basis gerakan radikal. Feminitas bukan tunduk, melainkan cara lain untuk melawan cara yang mengutamakan kehidupan, bukan kematian, perawatan, bukan penghancuran, solidaritas, bukan eksklusi.
Di tengah situasi politik yang semakin brutal, pink power menyingkap wajah sejati otoritarianisme. Ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak lahir dari kompromi elit, melainkan dari keberanian rakyat untuk merebut kembali ruang politik. Pink power adalah perlawanan terhadap tiga hal sekaligus, patriarki, kapitalisme, dan otoritarianisme. Ia menjawab domestikasi simbolik, eksploitasi ekonomi, dan represi politik. Pink power menegaskan bahwa perlawanan bisa lahir dari warna yang paling diremehkan, dari feminitas yang dianggap jinak, dari pengalaman sehari-hari yang penuh luka sekaligus kekuatan.
Pink melawan, bukan menunduk. Dan selama kekuasaan menindas, pink akan terus berkibar sebagai bendera perlawanan.
Penulis: Eva Nurcahyani
Daftar Pustaka:
- bell hooks. Feminism is for Everybody. South End Press, 2000.
- Federici, Silvia. Caliban and the Witch. Autonomedia, 2004.
- Ghodsee, Kristen R. & Mitchell A. Orenstein. Taking Stock of the Women’s March. Social Science Research Council, 2021.
- Gupta, Anjali. PINK: A Language of Communication for Feminism. IIP Series, Volume 3 Book 18, Futuristic Trends in Social Sciences, 2024.
- “The Indonesian feminist movement, between past and present.” https://www.politika.io/en/article/the-indonesian-feminist-movement-between-past-and-present, Politika.io, February 19, 2024.