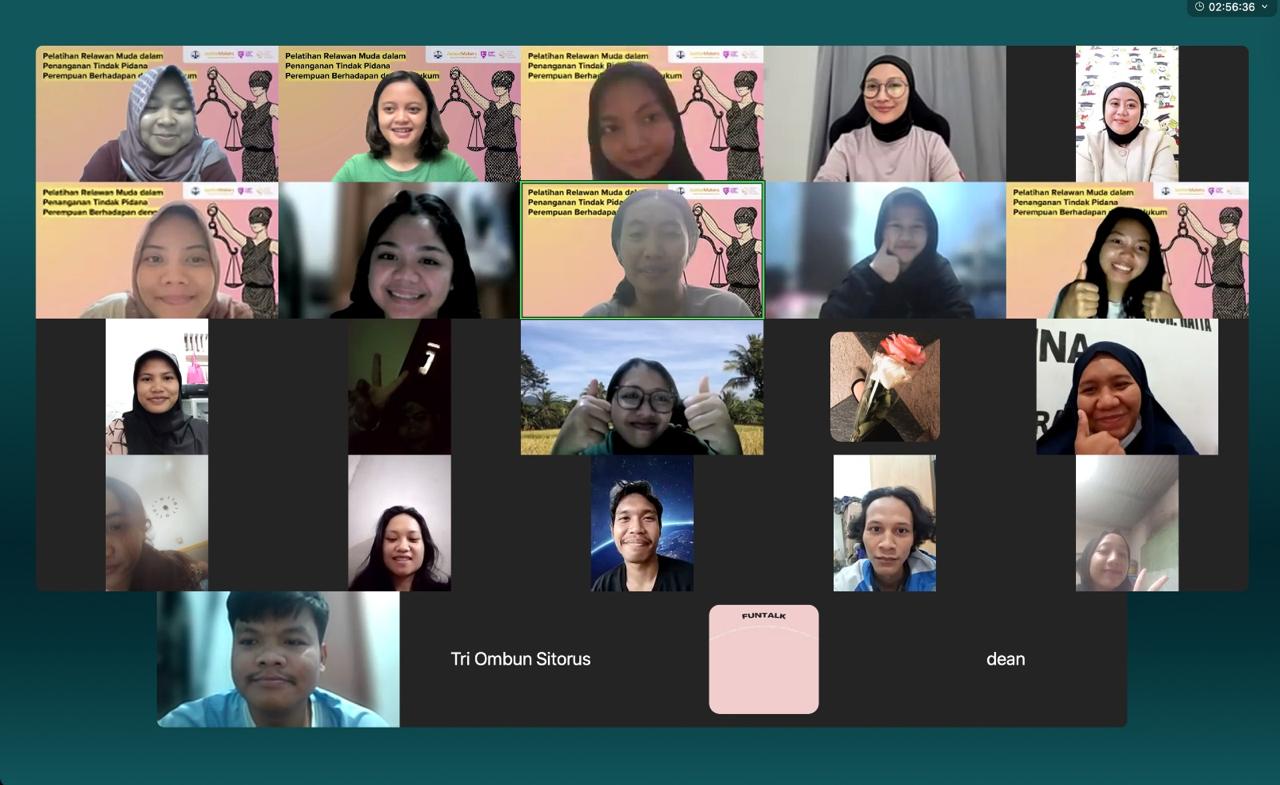Lingkar Studi Feminis bersama WCC Puantara baru-baru ini menyelenggarakan pelatihan dua hari yang memadukan pendekatan ilmiah dan kemanusiaan dalam penanganan anak dan perempuan berhadapan dengan hukum pada 8-9 November 2025. Hari pertama dihadiri oleh Novita Sari, Siti Mazmumah, dan rekan-rekan LSF, dengan materi “Teknik Konseling bagi Anak dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum” serta “Peran Pemuda dalam Pendampingan Anak dan Perempuan Berhadapan dengan Hukum.” Hari kedua menghadirkan AKBP Ema Rachmawati (Kanit PPA Mabes Polri) dalam sesi “Peran Pendamping Muda di Kepolisian” dan Siti Husna membawakan materi “Alur Penanganan Anak dan Perlindungan Hukum” (litigasi dan non-litigasi, termasuk mekanisme saat anak atau perempuan dikriminalisasi)
Tingginya Prevalensi Kekerasan, Rendahnya Pelaporan dan Penanganan Kasus
Menurut data nasional terbaru, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat luas terjadi. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 mencatat bahwa “satu dari empat perempuan Indonesia itu pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual… satu dari 5 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangan…”. Konteks ini menjadi latar belakang kuat mengapa pendampingan hukum dan psikososial sangat diperlukan. Beberapa pembicara menyoroti tantangan struktural: meski Kepolisian Indonesia memiliki Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), penanganan isu ini “tidak menjadi prioritas” dalam banyak program reformasi.
Dalam pemaparannya, Novita Sari menekankan bahwa korban kekerasan bukan pihak yang lemah, melainkan individu yang memiliki potensi untuk dipulihkan dengan pendekatan yang tepat. Ia menyoroti pentingnya menciptakan ruang aman, mendengarkan aktif, dan memberikan validasi emosional sebelum memasuki ranah hukum. Ia mengingatkan pendamping: “Jangan sampai korban datang mencari aman, tetapi justru mengalami ketidaknyamanan yang sama”
Diskusi peserta memperkuat konteks lapangan. Salah satu peserta mengangkat kasus teman yang dilecehkan namun tidak dipercaya lingkungan dan mengalami freeze, menandakan pentingnya edukasi publik mengenai respon trauma. Menanggapi hal tersebut, narasumber pun menegaskan bahwa respons freeze adalah reaksi biologis yang wajar dan bukan kesalahan korban, merujuk pada pengalamannya sendiri ketika menyaksikan tindak kriminal namun tubuhnya tidak mampu bereaksi.
Seorang peserta lain yang juga merupakan penyintas, menyoroti risiko burnout pada pendamping muda. Narasumber pun menekankan pentingnya perawatan diri (self-care) dan pembatasan beban kasus agar pendamping tidak menyalurkan emosi negatif kepada korban, yang dapat berdampak pada kualitas layanan.
Dalam pemaparannya, Siti Mazmumah menekankan bahwa orang muda memiliki peran strategis dalam pendampingan anak dan perempuan berhadapan dengan hukum. Ia menyoroti bahwa energi, keberanian, dan kedekatan emosional membuat orang muda lebih mudah dipercaya oleh korban, terutama korban yang juga berasal dari kelompok usia muda. “Anak muda itu percaya sama peer group-nya. Pendekatan sebaya membuat korban lebih nyaman untuk bercerita,” ujarnya.
Mazmumah juga mengangkat tantangan yang dihadapi pendamping muda. Ia menyebut bahwa legitimasi sering kali dipertanyakan oleh aparat penegak hukum karena usia atau latar belakang pendidikan. “Pendamping muda sering ditanya legitimasi oleh aparat, tapi komitmen dan empati kita adalah modal utama,” tegasnya. Selain itu, ia menekankan risiko trauma sekunder dan burnout yang nyata dalam pendampingan kasus kekerasan. “Trauma sekunder itu nyata. Kita harus punya mekanisme self-care agar tidak burnout,” tambahnya.
Diskusi peserta memperkuat konteks lapangan. Seorang peserta menyoroti bagaimana pendamping muda sering menghadapi intimidasi atau keraguan dari aparat. Menanggapi hal ini, Mazmumah menekankan pentingnya jaringan solidaritas dan dukungan komunitas. “Yang penting kita hadir dengan komitmen, empati, dan keberanian. Itu yang membuat kita dipercaya,” katanya.
Mazmumah juga menekankan bahwa peran orang muda tidak berhenti pada pendampingan langsung. Mereka dapat menjadi penggerak advokasi publik melalui media sosial, membentuk pos pengaduan di kampus atau komunitas, serta berkolaborasi dengan lembaga formal seperti UPTD PPA, LPSK, dan LBH. Dengan cara ini, orang muda tidak hanya mendampingi korban, tetapi juga memperkuat sistem perlindungan di tingkat komunitas.
Reformasi Struktural ke Ruang Aman: Strategi Pendampingan PBH
Hari kedua dari Pelatihan Relawan Muda dalam Penanganan Tindak Pidana Perempuan Berhadapan dengan Hukum menghadirkan Emma Rachmawati, Kanit PPA Mabes Polri, yang membawa sudut pandang kerja-kerja institusional kepolisian. Dalam pemaparannya, Emma Rachmawati menegaskan bahwa kepolisian tengah menghadapi lonjakan kasus perempuan dan anak yang semakin kompleks. “Kasus cenderung meningkat dan kompleksitasnya luar biasa. Struktur besar tidak menjamin kualitas, personil harus punya hati untuk PPA,” ujarnya. Ia menekankan bahwa peningkatan Unit PPA menjadi direktorat di tingkat Mabes Polri dan Polda bukanlah solusi tunggal, melainkan harus diiringi dengan pelatihan intensif dan penyederhanaan prosedur.
Emma menjelaskan bahwa mekanisme pelaporan kasus perempuan dan anak berbeda dengan tindak pidana umum. “Mekanismenya harus melalui PPA dulu. Harus dilakukan konseling oleh petugas PPA dulu, supaya kebutuhan korban jelas sejak awal,” katanya. Pendamping muda berperan penting dalam mendampingi korban sejak awal agar tidak merasa sendirian menghadapi aparat, mencegah reviktimisasi dengan memastikan korban tidak ditanya berulang kali, serta menghubungkan korban dengan layanan lain seperti UPTD PPA, rumah sakit, atau LPSK.
Ia juga memperkenalkan inovasi berupa sistem digital DORS dan program jemput bola. “Supaya laporan polisi terkait perempuan dan anak tidak lagi dibuat di SPKT, petugas PPA akan langsung membuat laporan di tempat itu melalui sistem DORS,” jelasnya. Program jemput bola memungkinkan petugas PPA mendatangi korban di rumah sakit atau rumah aman, sehingga korban tidak perlu datang ke kantor polisi. Pendamping muda diharapkan berperan dalam mengidentifikasi korban yang tidak mampu hadir, mengkoordinasikan kehadiran petugas, dan mendampingi korban selama proses jemput bola.
Dalam sesi tanya jawab, salah seorang peserta, Devi Sri Wahyuni mengangkat pertanyaan kritis: apakah peningkatan Unit PPA menjadi direktorat cukup untuk memperbaiki kualitas penanganan kasus, atau justru menambah beban birokrasi?
Menanggapi hal ini, Emma menjawab, “Struktur besar tidak menjamin kualitas. Reformasi harus diiringi pelatihan intensif dan kolaborasi lintas sektor.” Ia menambahkan bahwa tanpa kesiapan teknologi dan SDM yang merata, anggaran yang memadai-inovasi seperti DORS dan jemput bola berisiko hanya berjalan di kota besar, sementara daerah dengan kasus tinggi tetap tertinggal.
Setelah mendengar penjelasan Emma Rachmawati bahwa peningkatan Unit PPA menjadi direktorat harus diiringi pelatihan intensif dan kolaborasi lintas sektor, Devi Sri Wahyuni menanggapi dengan nada kritis. Menurutnya, jawaban tersebut masih terlalu normatif dan belum menyentuh akar persoalan.
Selanjutnya materi kedua dalam pemaparan Siti Husna adalah menekankan bahwa anak dan perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) merupakan kelompok yang paling rentan dalam sistem peradilan pidana. Mereka tidak hanya menghadapi prosedur hukum yang panjang dan formal, tetapi juga stigma sosial, diskriminasi, serta risiko kriminalisasi.
Husna menjelaskan bahwa jalur litigasi adalah proses formal yang ditempuh melalui kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Ketika anak atau perempuan menjadi korban tindak pidana, langkah pertama biasanya adalah pelaporan ke Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di kepolisian. Di sini dilakukan assessment awal, konseling, dan pengumpulan bukti. Namun, ia mengingatkan bahwa jalur litigasi sering kali tidak cukup. “Banyak korban yang tidak siap menghadapi proses hukum panjang. Karena itu, jalur non litigasi seperti mediasi dan pendampingan psikososial menjadi pintu pemulihan yang lebih cepat”, tegasnya.
Selain itu, Husna menyoroti risiko kriminalisasi terhadap korban. Ia memberi contoh kasus di mana perempuan yang melawan justru dijadikan tersangka. “Kita harus kritis, karena tidak jarang perempuan yang melawan justru dikriminalisasi. Pendamping wajib memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi”, katanya. Ia menekankan bahwa anak sebagai pelaku pun tetap memiliki hak atas pendidikan, rehabilitasi, dan perlakuan khusus sesuai kondisi.
Diskusi peserta memperkuat konteks lapangan. Seorang peserta menanyakan bagaimana pendamping bisa menghadapi aparat yang tidak berpihak. Husna menjawab dengan tegas, “Walaupun sudah ada Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak di Mabes Polri, kenyataannya isu ini masih belum jadi prioritas. Itu yang harus kita kawal bersama.” Ia menambahkan bahwa pendamping muda harus berani bersuara, membangun jaringan, dan mengawal kasus hingga selesai agar korban tidak kehilangan haknya.
Kontributor : Irhamna