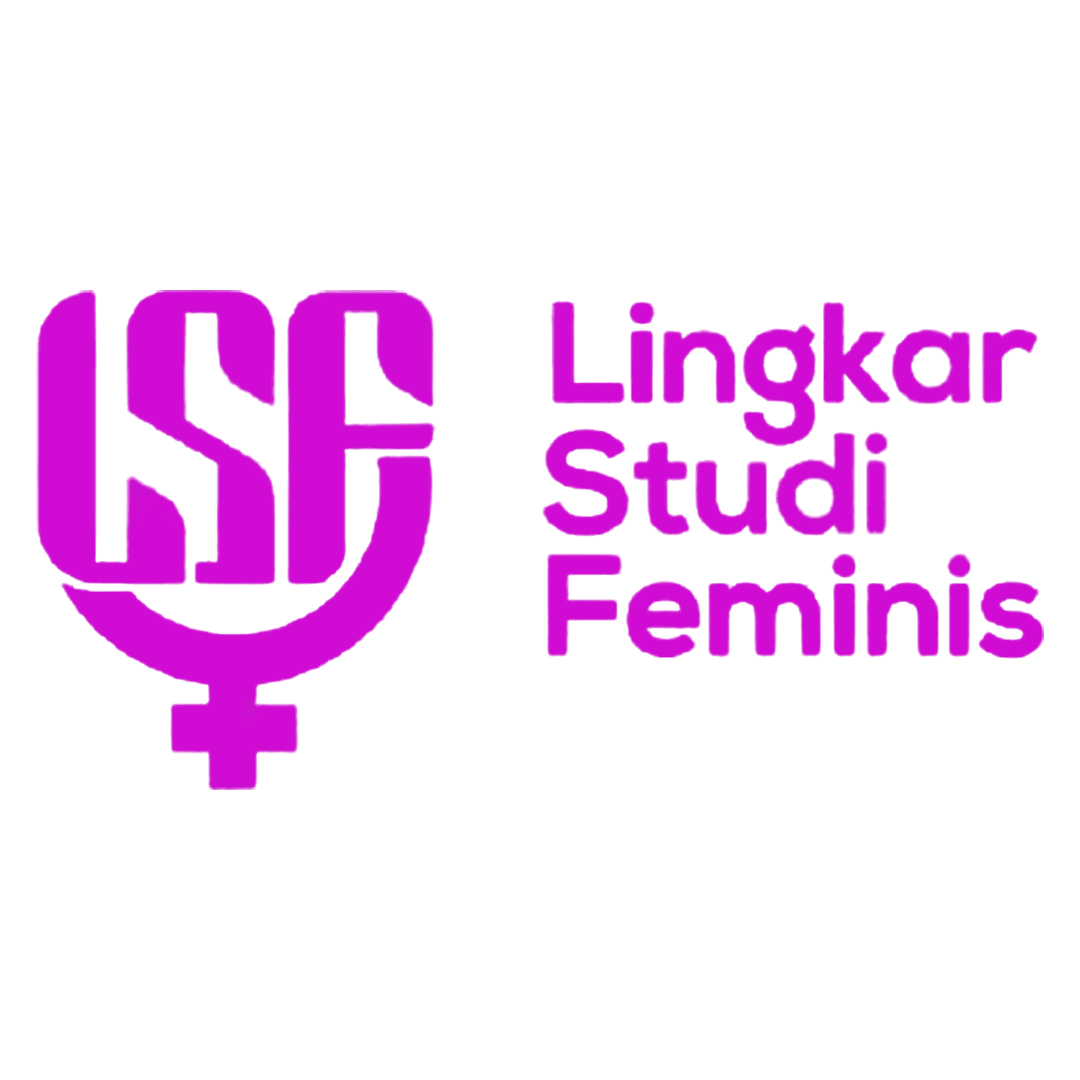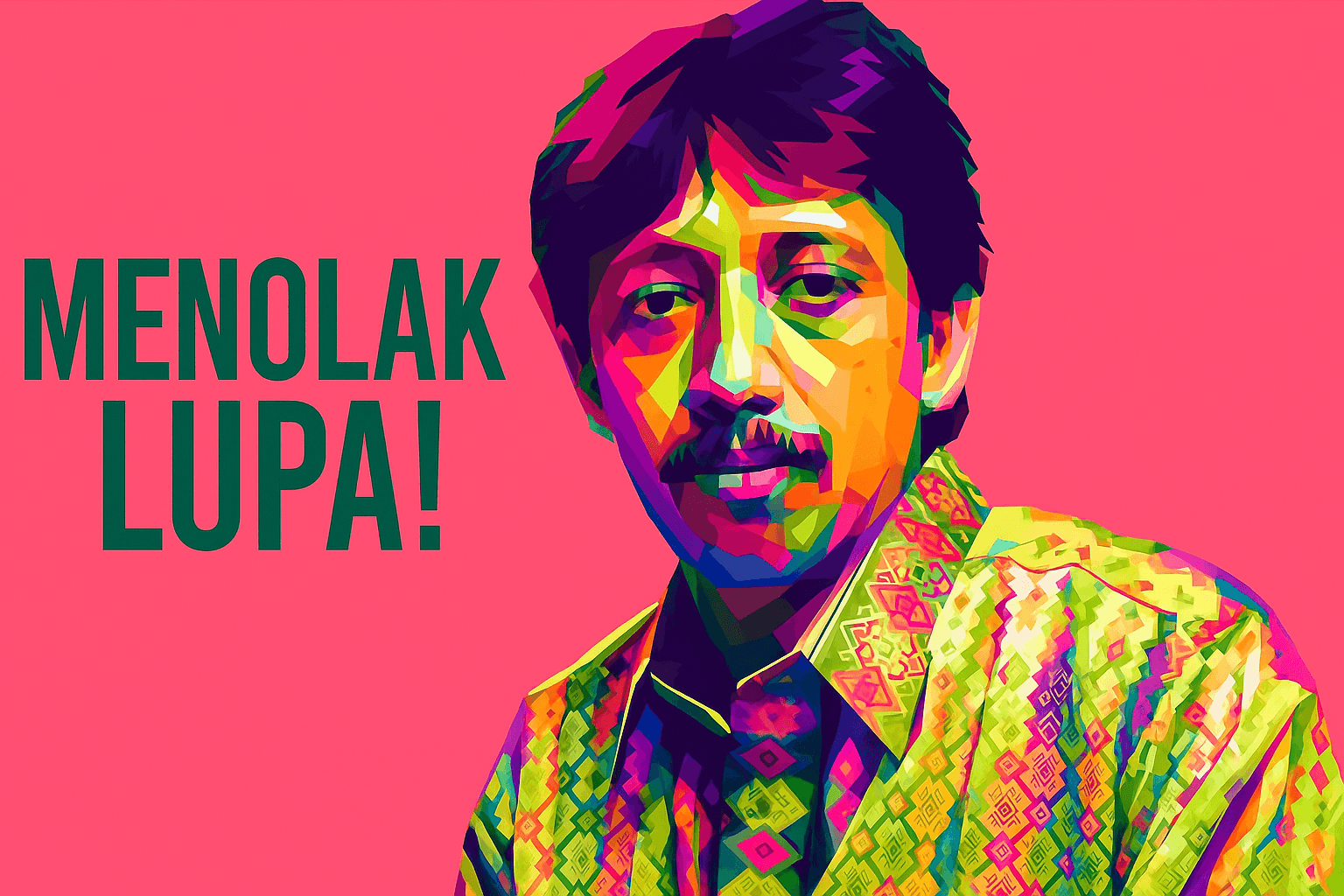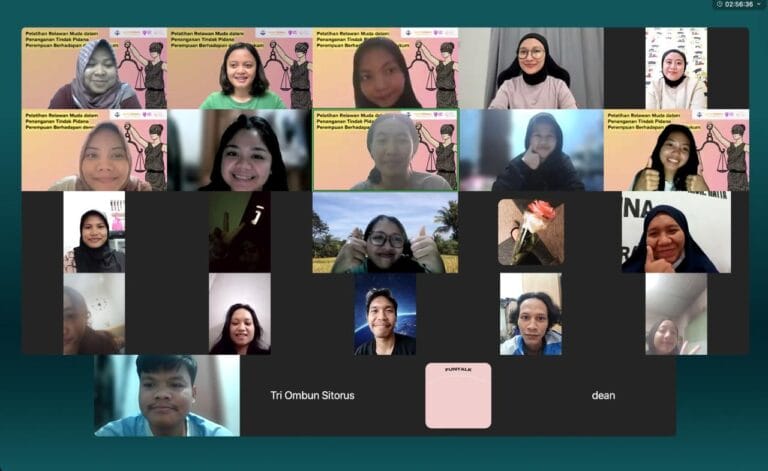Di negeri ini, luka bukan sekadar jejak masa lalu. Ia adalah bukti material tentang bagaimana negara bekerja, siapa yang dilindungi, siapa yang dikorbankan. Luka kolektif yang kita simpan hari ini bukanlah nostalgia penderitaan, melainkan peta kekerasan yang diwariskan oleh sebuah rezim yang berdiri di atas impunitas.
Kasus pembunuhan Munir menelanjangi itu semua. Ia tidak mati di medan perang, melainkan di udara, ruang yang katanya paling steril. Ia dibunuh bukan karena memegang senjata, tetapi karena membawa kebenaran tentang praktik penyiksaan, penghilangan paksa, dan teror negara. Yang disingkirkan bukan hanya seorang individu, melainkan sebuah kemungkinan, bahwa Indonesia bisa dibangun tanpa menggadaikan hukum kepada aparat kekerasan.
Namun kematian Munir tidak pernah dituntaskan. Negara memilih melindungi pelaku dengan prosedur hukum yang cacat, dengan peradilan yang sengaja dibonsai. Hasilnya, luka itu tidak pernah hilang. Ia berulang dalam wajah-wajah baru, mahasiswa yang ditendang di jalan, petani yang dipenjara karena mempertahankan tanah, buruh yang diintimidasi aparat, suporter bola yang meregang nyawa karena gas air mata. Polanya sama, kekerasan dijadikan instrumen untuk mengamankan kepentingan politik-ekonomi, sementara korban direduksi menjadi “oknum salah tempat”.
Dua puluh satu tahun setelah Munir dibunuh, yang kita saksikan bukan penyelesaian, melainkan pengulangan. Dua puluh satu tahun pembunuhan Munir tetap ada, bahkan berlipat ganda, dari satu tubuh ke ribuan tubuh lain, dari satu tragedi ke berbagai peristiwa represi yang menumpuk. Munir tidak sekadar hilang di masa lalu, ia hadir di setiap luka baru yang diproduksi negara.
KontraS dalam laporan 20 Tahun Munir (2024) menegaskan “Kasus pembunuhan Munir adalah cermin dari praktik impunitas di Indonesia. Negara gagal mengungkap aktor intelektual, dan kegagalan ini membuka jalan bagi pengulangan kekerasan, intimidasi, dan pembungkaman terhadap warga negara hingga hari ini.” Fakta ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya abai, tetapi aktif merawat impunitas sebagai bagian dari cara berkuasa.
Di sinilah trauma kolektif bekerja. Ia bukan sekadar perasaan tertekan yang diwariskan, melainkan kesadaran politik yang tajam. Trauma membuat kita membaca peta kekuasaan tanpa ilusi. Kita tahu bahwa negara tidak netral; ia berdiri di pihak modal dan aparat. Ia menjadikan hukum sebagai alat represi, bukan perlindungan.
Bagi keluarga korban atau komunitas yang terus ditindas, trauma adalah kompas politik. Seorang ibu yang kehilangan anak di stadion tidak lagi percaya pada janji kampanye. Ia tahu bahwa negara selalu memunggungi warganya. Trauma membuat kita berhenti menunggu, berhenti berharap pada elite, dan mulai membangun orientasi politik dari bawah, solidaritas, organisasi, dan perlawanan kolektif.

Itulah yang membuat trauma berbahaya bagi penguasa. Ia tidak bisa ditutup arsip, tidak bisa dipadamkan dengan peringatan seremonial. Trauma melekat pada tubuh, dalam rasa gentar ketika melihat aparat, dalam kemarahan yang muncul saat mendengar kabar kriminalisasi, dalam kegigihan untuk menolak lupa. Trauma menjelma kekuatan, energi yang mengikat komunitas korban dengan gerakan sosial yang lebih luas.
Karena itu, luka kolektif tidak boleh dikelola hanya sebagai duka. Ia harus dipolitisasi. Sebab tanpa itu, trauma hanya berputar dalam spiral, menjadi beban yang membeku. Tetapi jika ia dijadikan dasar orientasi, trauma bisa berubah menjadi senjata politik, menguji siapa yang berpihak, siapa yang menipu; siapa yang membela hidup, siapa yang terus mengulang kekejaman.
Di tengah krisis demokrasi hari ini, ketika otoritarianisme lama bersemi kembali dengan wajah baru, trauma kolektif adalah satu-satunya orientasi yang jujur. Ia menuntun kita pada pilihan yang jelas, melawan, atau ikut mengaburkan ingatan.
Maka, luka Munir bukan hanya sejarah. Ia adalah senjata. Senjata untuk menantang negara yang dibangun di atas impunitas, dan untuk merumuskan politik rakyat yang bertumpu pada ingatan, keberanian, dan solidaritas.
Penulis : Eva Nurcahyani
Daftar Pustaka:
- Hadiz, Vedi R. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia, A Southeast Asia Perspective, Stanford University Press, 2010.
- Human Rights Watch. Unkept Promise, Failure to End Military Business Activity in Indonesia, HRW Report, 2010.
- KontraS. 20 Tahun Munir: Negara Masih Ingkar Kebenaran dan Keadilan. Laporan Tahunan, 2024.
- Robert, Robertus. Otoritarianisme dan Perlawanan: Gerakan Demokrasi di Indonesia. LP3ES, 2020.
- Tempo. The Last Flight: Investigasi Majalah Tempo atas Kematian Munir. Tempo Publishing, 2005.